periskop.id - Satu ledakan mengguncang SMA Negeri 72 Jakarta. Polisi turun tangan, media ramai memberitakan. Namun, di balik rentetan fakta, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam tentang bagaimana bisa korban menjadi pelaku?
Jawabannya tidak sesederhana dendam, melainkan persoalan psikologis dan sosial yang mengakar, mulai dari pengucilan hingga kurangnya empati di lingkungan sekolah.
Fakta Kasus Ledakan di SMA 72 Jakarta dan Potret Buram Dunia Sekolah
Pagi yang seharusnya diwarnai tawa dan doa di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta berubah menjadi kepanikan. Dentuman keras memecah suasana, meninggalkan puluhan siswa dan guru luka-luka hingga 96 orang menurut laporan awal pihak kepolisian.
Lalu, yang lebih mengejutkan lagi, pelakunya diduga bukan orang luar, melainkan salah satu siswa sekolah itu sendiri.
Kepolisian masih mendalami motif, tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengindikasikan adanya tekanan sosial dan kemungkinan pengaruh dari konten media yang memperburuk kondisi psikologis pelaku.
Menurut data resmi KPAI, hingga Maret 2024 terdapat 383 kasus pengaduan pelanggaran perlindungan anak dan 34% merupakan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Lebih parah lagi, laporan NU Online mencatat bahwa 3.800 anak di Indonesia mengalami trauma psikologis sepanjang 2023 akibat kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah.
Angka-angka itu tak lagi bisa dianggap statistik semata karena di balik setiap kasus, ada wajah yang terluka, ada anak yang kehilangan rasa aman, dan ada sistem pendidikan yang gagal menjadi tempat perlindungan.
Perundungan bukan sekadar kenakalan remaja. Ia adalah bom waktu psikologis yang bisa meledak kapan saja jika tidak segera ditangani dengan empati, perhatian, dan perubahan nyata di ruang-ruang kelas.
Analisis Psikologis Korban Menjadi Pelaku
Kasus SMA 72 Jakarta menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah tak selalu datang dari luar. Kadang, ia tumbuh pelan di dalam diri seseorang yang terlalu lama menahan luka. Dari sinilah proses psikologis itu dimulai, bagaimana tekanan sosial bisa mengikis rasa percaya diri dan mengubah arah emosi seseorang.
1. Rasa Pengucilan dan Identitas yang Terkikis
Ketika ejekan datang berulang tanpa tempat berlindung, frustrasi berkembang menjadi keputusasaan. Korban merasa bahwa tidak ada yang bisa menolong sehingga emosi terpendam mencari jalan keluar sendiri.
Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024) terhadap 612 siswa korban bullying di Surabaya menunjukkan bahwa lemahnya dukungan sosial membuat korban cenderung menarik diri dan kehilangan kemampuan mengatur emosi.
Temuan serupa juga datang dari Universitas Islam Indonesia (2023) yang mencatat banyak korban bullying menyalurkan rasa marah melalui media sosial atau diam hingga akhirnya berbalik menjadi pelaku.
2. Frustrasi dan Ketidakmampuan Mengelola Emosi
Ketika ejekan datang berulang tanpa tempat berlindung, frustrasi berkembang menjadi keputusasaan. Korban merasa bahwa tidak ada yang akan menolong sehingga emosi terpendam mencari jalan keluar sendiri. Dalam beberapa kasus, mereka mulai menarik diri, menulis hal-hal gelap, atau mencari pelampiasan di dunia maya, gejala yang sering diabaikan guru dan orang tua.
Penelitian di Indonesia menemukan bahwa regulasi emosi korban bully sangat berperan dalam dampaknya. Studi “Resilience in Adolescent Victims of Bullying: The Role of Emotion Regulation and Social Support” pada 612 korban bullying usia 13–15 tahun di Surabaya menunjukkan bahwa kemampuan mengatur emosi dan dukungan sosial terbukti secara signifikan meningkatkan resiliensi korban.
3. Normalisasi Kekerasan dan Pengaruh Lingkungan
Faktor lain yang tak kalah penting adalah lingkungan yang permisif. Ketika ejekan dianggap candaan atau kekerasan dianggap bumbu pergaulan, batas moral jadi kabur.
Kasus SMA 72 Jakarta memperlihatkan bagaimana media sosial juga dapat memperburuk situasi. Menurut KPAI, pelaku diduga terpapar konten ekstrem yang memperkuat rasa dendam dan keinginan untuk membalas.
Ketika Korban Berubah Jadi Pelaku
Di balik setiap kasus bullying di sekolah, ada kisah yang lebih rumit dari sekadar pelaku dan korban. Beberapa korban justru tumbuh menjadi pelaku baru, mewarisi luka yang tak pernah disembuhkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa bullying bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga rantai psikologis yang terus berputar di lingkungan pendidikan.
Penelitian dari Universitas Raden Fatah Palembang (Nugroho dkk., 2021) mengungkap bagaimana perubahan itu terjadi secara bertahap. Korban yang awalnya menahan sakit hati akan melalui fase frustrasi dan coping maladaptif, sebuah mekanisme untuk melindungi diri, tapi sering berujung pada perilaku agresif terhadap orang lain.
Hasil serupa juga ditemukan dalam studi Makgatho Health Sciences University (2024) di Afrika Selatan. Peneliti mencatat bahwa banyak korban mulai mem-bully siswa lain yang dianggap lebih lemah sebagai bentuk perlindungan diri, menciptakan siklus kekerasan baru yang sulit dihentikan.
Kedua riset ini menegaskan satu hal penting bahwa korban yang tidak mendapat dukungan emosional dari guru, teman, atau keluarga, berisiko kehilangan empati dan meniru perilaku yang dulu melukai mereka.
Luka yang Tak Diobati Bisa Menjadi Ledakan
Polanya sering sama, dimulai dari menjadi korban, menanggung tekanan tanpa dukungan, kehilangan kontrol, dan tindakan ekstrem.
Tentu saja, tidak semua korban akan menjadi pelaku. Namun, ketika sistem sekolah dan keluarga gagal mengenali sinyal bahaya, peluang tragedi meningkat.
Artinya, masalah ini bukan hanya milik satu sekolah, melainkan cermin dari sistem sosial yang kehilangan empati.
Jika anak-anak tumbuh dalam ketakutan tanpa ruang aman untuk bicara, maka kita sedang menanam bibit kekerasan generasi berikutnya.





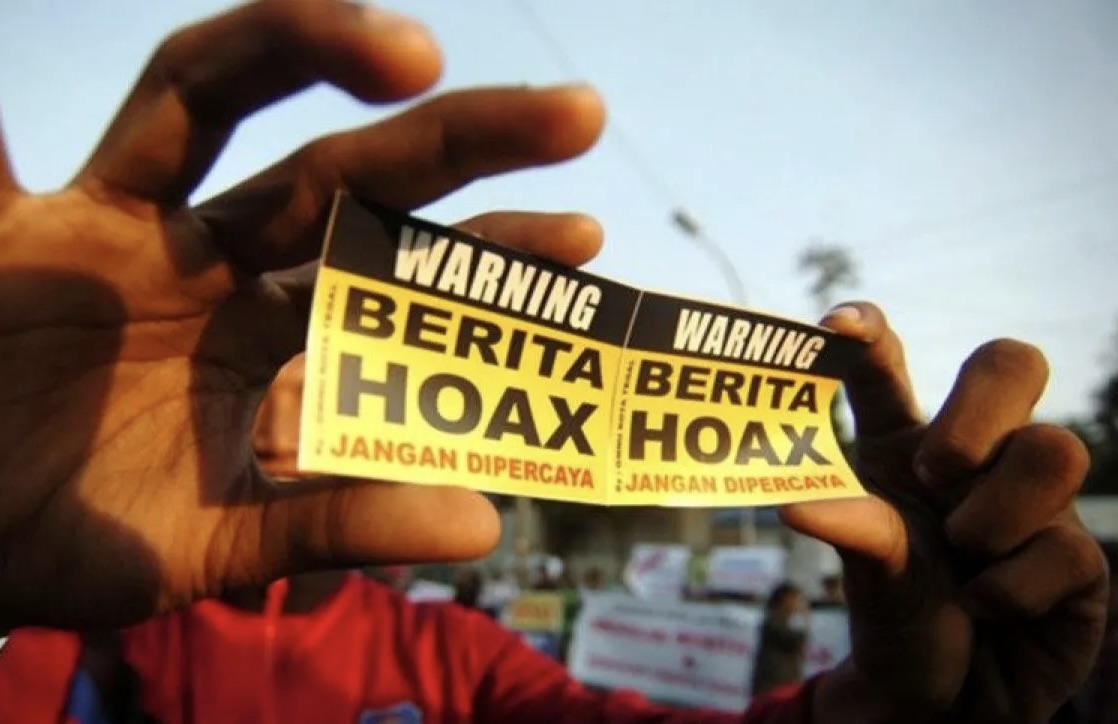



Tinggalkan Komentar
Komentar