periskop.id - Belakangan ini, diskusi mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali memanas. Ada sebagian elit politik yang menyuarakan wacana untuk mengembalikan mandat Pilkada ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasan yang mereka gaungkan terdengar sangat mulia, Pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan, memicu polarisasi di tengah masyarakat, dan ini poin yang paling sering dijadikan tameng, rakyat dianggap terlalu pragmatis sehingga memicu suburnya praktik politik uang.
Narasi yang dibangun seakan memosisikan partai politik dan anggota dewan sebagai entitas paling berintegritas untuk menekan ongkos demokrasi. Argumen utamanya adalah pemilihan melalui perwakilan dianggap lebih terukur dan steril dari praktik politik uang di tingkat masyarakat. Akan tetapi, sebelum kita tergesa-gesa mengamini wacana tersebut, sangat krusial bagi kita untuk melakukan verifikasi silang dengan realitas data yang sebenarnya.
Apakah benar para pengusul perubahan ini memiliki rekam jejak integritas yang cukup mumpuni untuk diberikan kepercayaan sebesar itu? Atau jangan-jangan, ini hanya strategi memindahkan loket transaksi dari ruang terbuka ke ruang tertutup?
Niat Memperbaiki Sistem atau Menutupi Jejak Hitam?
Sebuah ironi besar mencuat di tengah wacana politik terkini. Partai-partai yang menyatakan dukungan penuh agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, ternyata memiliki rekam jejak yang mengkhawatirkan. Niat perbaikan sistem yang mereka gaungkan seolah runtuh seketika. Mengapa? Karena di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024, kader dari partai-partai tersebut justru terjerat berbagai kasus korupsi.
Sulit memercayai niat perbaikan sistem saat para aktornya memiliki rekam jejak integritas yang buruk. Data olahan Bijak Memilih yang bersumber dari KPK dan ICW, mengungkap fakta keras, partai-partai besar di parlemen justru menjadi penyumbang signifikan kasus korupsi.
Mari kita bedah angkanya. Partai Golkar memimpin daftar ini dengan jumlah kasus yang mencengangkan, yakni 64 kasus suap dan gratifikasi dengan total nominal mencapai Rp280 miliar. Tidak jauh di belakangnya, ada Partai NasDem dengan 18 kasus, tetapi nilai nominalnya sangat fantastis, yakni Rp224 miliar. Partai Amanat Nasional (PAN) juga memiliki catatan 28 kasus dengan total Rp195 miliar.
Daftar ini terus berlanjut. Partai Demokrat mencatatkan 48 kasus dengan nilai Rp119 miliar, disusul Partai Gerindra dengan 23 kasus senilai Rp62,3 miliar, dan PKB dengan 18 kasus senilai Rp35,8 miliar. Jika kita menjumlahkan total nominal uang negara yang dimainkan melalui suap dan gratifikasi dari keenam partai ini saja, angkanya menembus lebih dari Rp900 miliar. Angka ini menjadi bukti valid bahwa penyakit transaksional justru sangat kronis di tubuh partai politik itu sendiri.
Lebih Mudah Suap 50 Anggota Dewan daripada 1 Juta Rakyat
Melihat data di atas, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD menjadi sebuah ironi yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita menyerahkan hak memilih pemimpin daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota kepada institusi yang diisi oleh partai-partai dengan rekam jejak korupsi ratusan miliar rupiah? Jika alasan mencabut Pilkada langsung adalah untuk menghilangkan politik uang di masyarakat, data di atas justru mengindikasikan risiko yang jauh lebih mengerikan, yaitu sentralisasi korupsi.
Logikanya sederhana. Dalam Pilkada langsung, calon kepala daerah harus meyakinkan ratusan ribu hingga jutaan rakyat. Meskipun praktik serangan fajar masih terjadi, menyuap jutaan orang adalah hal yang logistiknya sangat rumit dan mahal. Namun, jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, seorang calon kepala daerah hanya perlu melobi puluhan anggota dewan. Dengan rekam jejak suap dan gratifikasi yang sudah ada, potensi transaksi politik di ruang tertutup gedung dewan menjadi sangat tinggi.
Alih-alih menghasilkan pemimpin yang kompeten, sistem ini berisiko besar melahirkan pemimpin yang pandai membeli tiket rekomendasi partai. Jika kader partai saja sudah terbiasa dengan kasus suap bernilai miliaran rupiah saat ini, bayangkan apa yang terjadi jika mereka memegang kekuasaan penuh untuk menunjuk kepala daerah tanpa campur tangan rakyat. Ini bukan lagi soal efisiensi anggaran pemilu, melainkan soal potensi pembajakan demokrasi oleh oligarki partai yang memiliki rapor merah dalam pemberantasan korupsi.
Benahi Dulu Integritas, Baru Bicara Mandat
Pada akhirnya, data ini menjadi peringatan keras bagi publik. Wacana Pilkada oleh DPRD tidak boleh diterima begitu saja tanpa sikap kritis. Masalah utama dalam demokrasi kita hari ini mungkin bukan pada siapa yang memilih, melainkan pada integritas para aktor politiknya. Selama partai politik belum mampu mendisiplinkan kadernya dan membersihkan diri dari praktik suap serta gratifikasi, segala bentuk perubahan sistem pemilihan hanya akan menjadi jalan baru bagi praktik korupsi.
Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus menuntut partai politik untuk melakukan reformasi internal terlebih dahulu sebelum meminta wewenang lebih besar. Jangan sampai kita menyerahkan kunci rumah kita kepada pihak yang rekam jejaknya justru meragukan.




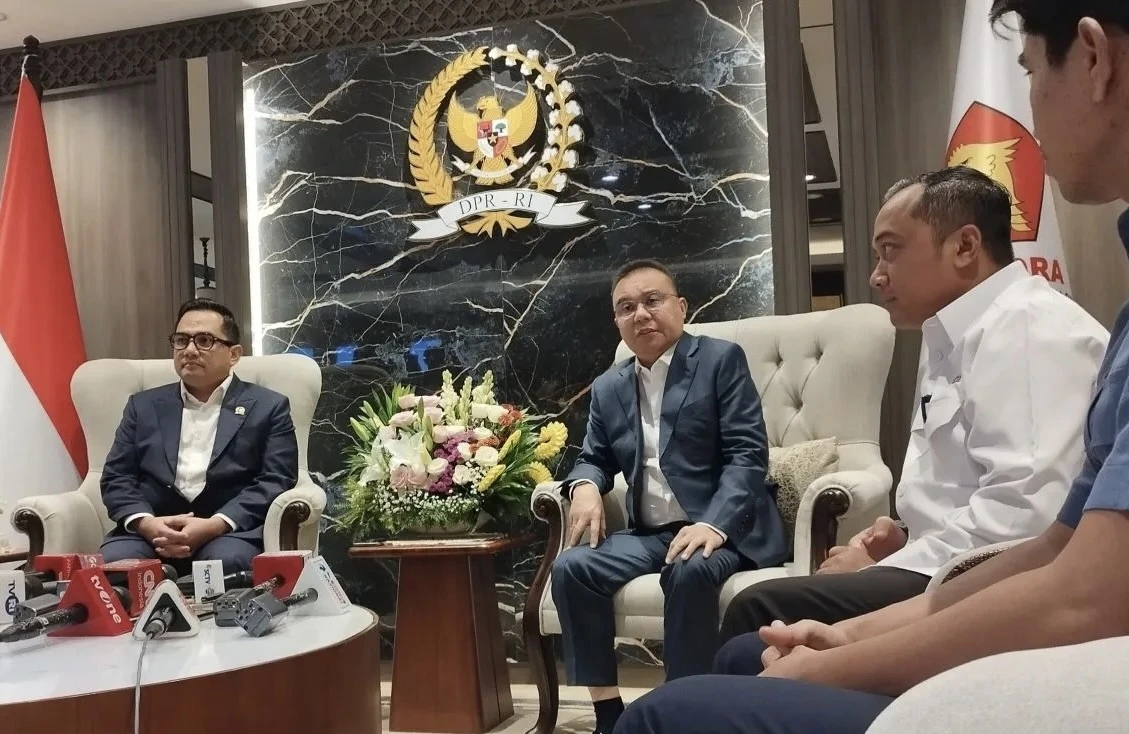

Tinggalkan Komentar
Komentar