periskop.id – Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD dinilai sebagai diagnosis yang keliru dalam upaya membenahi sengkarut demokrasi di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia.
“Argumen ini sekilas terdengar masuk akal dan memang ada benarnya. Akan tetapi, demokrasi itu bukanlah jalan pintas. Ia penuh prosedur, berisik, ribut, dan sering bikin capek. Tapi justru di situ wataknya,” kata Alfath kepada Periskop, Sabtu (10/1).
Alfath membedah narasi yang kerap didengungkan oleh sejumlah elite partai, yakni demokrasi saat ini dianggap terlalu melelahkan, berantakan, dan berbiaya tinggi. Namun, alasan tersebut dinilai tidak valid untuk melegitimasi pemangkasan hak politik rakyat.
Menurutnya, sistem demokrasi memang sengaja didesain sedemikian rupa agar kekuasaan tidak menumpuk pada segelintir orang. Sayangnya, kondisi internal partai politik di parlemen justru menunjukkan tren yang memburuk dengan pola kekuasaan yang cenderung oligarkis atau "4L" (Lu Lagi Lu Lagi).
Dari delapan partai politik yang bercokol di Senayan, Alfath mengamati enam di antaranya memiliki sistem demokrasi internal yang buruk. Sirkulasi kekuasaan tidak berjalan sehat, kecuali Partai Golkar dan PKS yang dinilai relatif lebih baik dalam aspek tersebut.
Terkait isu biaya tinggi, akademisi UGM ini meluruskan kesalahpahaman publik. Sumber mahalnya ongkos demokrasi bukan terletak pada sistem pemilihan langsung atau hak pilih warga, melainkan perilaku koruptif para elite politik.
“Apa yang sebenarnya mahal dari demokrasi kita? Bukan hak pilih rakyatnya, bukan pilkada langsungnya. Yang membuat mahal itu adalah perilaku elit politiknya yang lebih mengedepankan mahar, jual-beli suara, relasi patron-klien, bahkan minimnya pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Biaya politik makin membengkak karena adanya praktik korupsi pascapemilihan. Hal ini biasanya terkait erat dengan eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam oleh para pejabat terpilih demi "balik modal".
Oleh karena itu, solusi mengembalikan Pilkada ke DPRD dianggap sangat tidak tepat sasaran. Alfath mengibaratkan langkah ini seperti mengobati pasien yang salah, di mana penyakitnya ada di tubuh elite, namun yang "diamputasi" justru partisipasi rakyat.
Ia tidak menampik bahwa pemilihan tidak langsung bisa menghemat anggaran negara dan mengurangi keriuhan kampanye. Namun, demokrasi yang sunyi dan "murah" tersebut berisiko mematikan ruang partisipasi publik yang substantif.
“Lelah itu konsekuensi dari keterlibatan. Rakyat capek karena ikut menentukan, bukan karena sekadar jadi penonton,” tegas Alfath.
Jika skema pemilihan via DPRD benar-benar diterapkan, pihak yang paling diuntungkan adalah partai-partai besar dan oligarki lokal. Bandul kekuasaan akan bergeser menjauh dari rakyat, membuat kepala daerah lebih sibuk melayani fraksi di DPRD ketimbang konstituennya.
Praktik kotor politik uang pun tidak akan hilang, melainkan hanya berpindah tempat. Transaksi yang tadinya terjadi di lapangan terbuka saat kampanye massal, akan beralih ke lobi-lobi tertutup yang sulit diawasi.
“Politik transaksional tidak hilang, hanya bergeser dari lapangan terbuka ke ruang-ruang tertutup, dari kampanye massal ke lobi elite. Ini pengalaman lama di era sebelum pemilu, dan kita tahu betul bagaimana praktiknya waktu itu,” ingatnya.
Alfath memperingatkan bahwa wacana ini sejatinya bukan tentang efisiensi, melainkan redistribusi kekuasaan. Mengurangi peran rakyat dalam memilih pemimpinnya bukan perbaikan demokrasi, melainkan sebuah kemunduran besar yang dibungkus dengan alasan teknis.
“Kalau itu tidak dibenahi, mau pilkada langsung atau tidak langsung, yang diuntungkan tetap elite, sementara masyarakat tetap berada dalam posisi inferior di sepanjang kehidupan mereka,” pungkas Alfath.




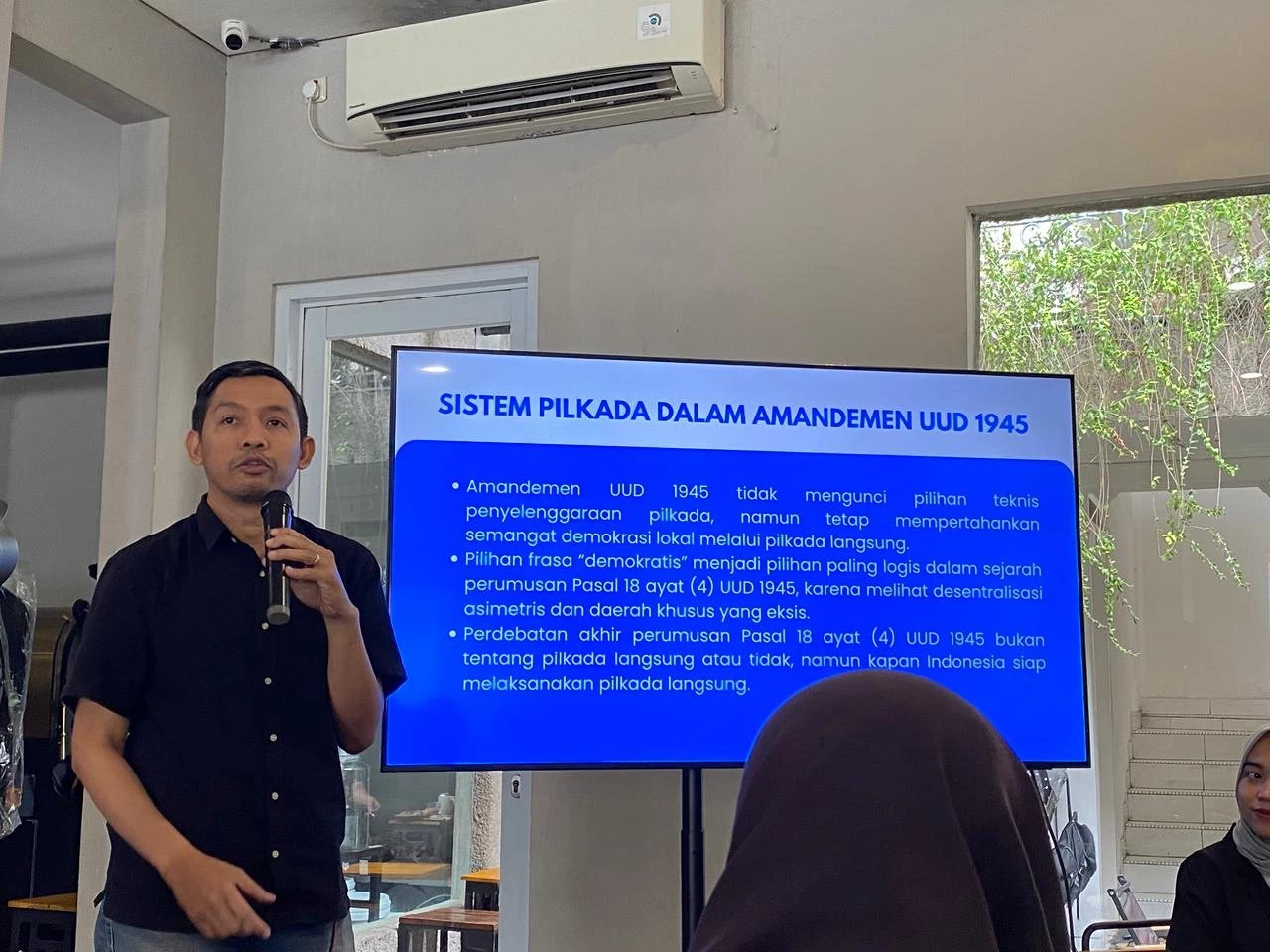
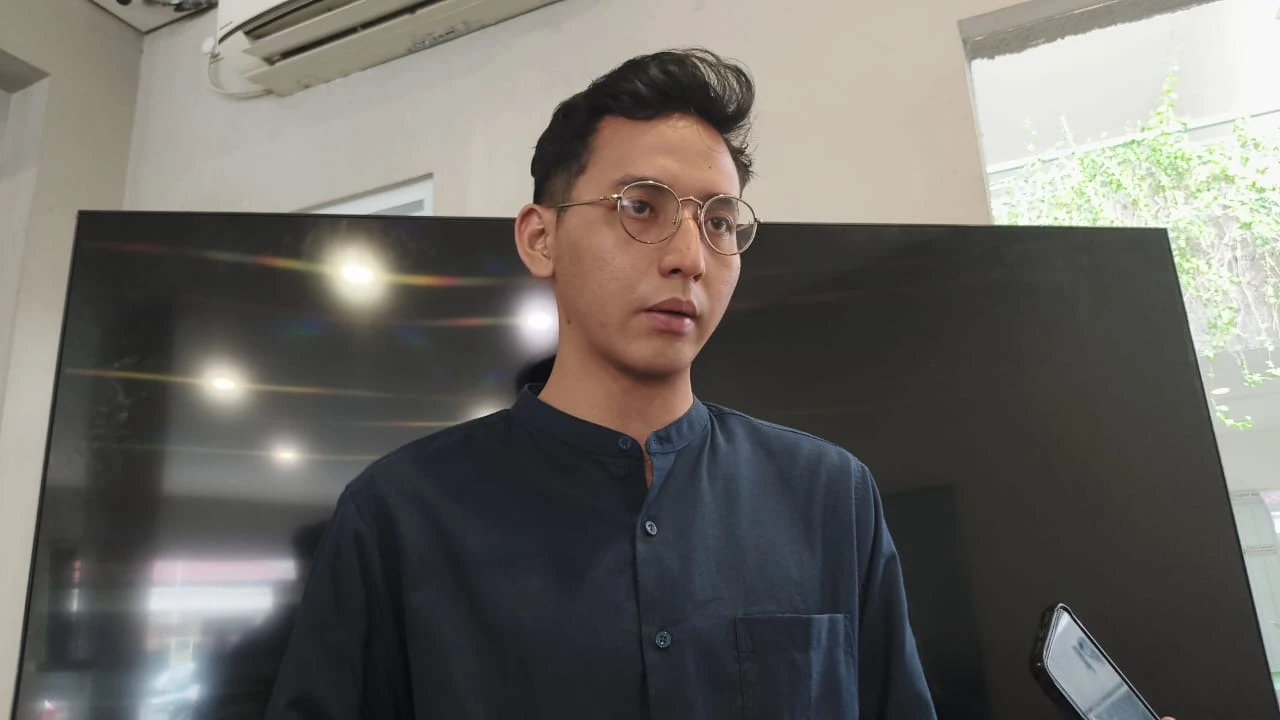



Tinggalkan Komentar
Komentar