periskop.id - Direktur sekaligus Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa mengungkapkan sejumlah faktor utama yang membuat publik tetap menghendaki pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung dan menolak wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Berdasarkan hasil riset LSI, penolakan publik terhadap pilkada DPRD bersifat kuat, masif, dan sistemik.
Alasan pertama, menurut Ardian, berkaitan dengan memori kolektif masyarakat selama sekitar 20 tahun terakhir. Ia menjelaskan, pilkada langsung telah dijalankan sejak 2005, sedangkan pemilihan presiden secara langsung sudah berlangsung sejak 2004. Selama dua dekade, masyarakat Indonesia telah terbiasa memilih pemimpinnya secara langsung.
“Minimal 20 tahun terakhir rakyat sudah terbiasa memilih langsung. Sehingga jika sekarang tiba-tiba berubah, apalagi dengan perubahan yang tidak berdasar pada asumsi-asumsi yang bisa diterima publik, tentu penolakannya akan keras,” kata Ardian, di Kantor LSI, Rabu (7/1).
Ardian menambahkan, pemilihan langsung dianggap sebagai satu-satunya cara yang wajar untuk memilih kepala daerah, bukan melalui mekanisme pilihan atau lobi elite. Pilkada langsung telah menjadi pesta rakyat di berbagai daerah karena masyarakat merasa bergembira dapat menentukan pemimpinnya sendiri tanpa perantara. Kebiasaan demokrasi ini membentuk persepsi kuat pemilihan langsung adalah bagian hak politik yang tidak bisa begitu saja dihapus.
Alasan kedua adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD. Ardian menjelaskan, berbagai survei menunjukkan DPRD dan DPR secara konsisten masuk dalam kelompok lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah.
“Bahkan, angka trust publik ke DPRD dan DPR sekitar 50%, jauh di bawah lembaga lain yang bisa mencapai tingkat kepercayaan 80-90%,” ujar dia.
Selain itu, DPRD kerap diasosiasikan dengan politik transaksional, baik yang terjadi “di bawah meja maupun di atas meja”. Persepsi publik terhadap korupsi legislatif juga masih tinggi. Bahkan, masyarakat menganggap partai politik dan DPRD sebagai “sarang korupsi”, meskipun hal tersebut diakuinya sebagai persepsi yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ardian juga menyoroti kekhawatiran publik terhadap partai politik yang dapat memaksakan calon kepala daerah tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Bahkan, calon tersebut juga bisa jadi tidak dikenal oleh publik di daerahnya. Hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan terhadap mekanisme pilkada melalui DPRD.
“Kemudian juga persepsi korupsi legislatif masih tinggi, kita tidak bisa memungkiri banyak sekali persepsi yang berkembang partai politik anggota DPRD persepsi itu dianggap sebagai ‘sarang korupsi’ ini persepsi yang berkembang di masyarakat ya tentu ini juga menjadi PR bukan hanya buat politisi-politisi, tapi juga buat kita semuanya,” jelas dia.
Alasan ketiga berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik. Ardian menegaskan, seseorang tidak bisa menjadi anggota DPRD tanpa melalui partai politik, sedangkan kepercayaan publik terhadap partai juga masih rendah. Dalam survei LSI, hanya 53,3% responden yang percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sedangkan 39,3% menyatakan tidak percaya.
“Partai politik adalah salah satu lembaga yang secara konsisten berada di kelompok dengan tingkat kepercayaan publik terendah dibandingkan pilar-pilar demokrasi lainnya,” tutur Ardian.
Alasan keempat, faktor paling dominan, adalah pandangan publik tentang pilkada langsung yang merupakan hak rakyat, bukan proses elit. Ardian mengungkapkan, ketika alasan penolakan digali lebih dalam, sebanyak 82,2% responden menolak pilkada DPRD karena dinilai menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Alasan kelima adanya rasa kontrol (sense of control) yang dirasakan publik dalam pilkada langsung. Ardian menambahkan, masyarakat merasa memiliki hubungan langsung dengan kepala daerah yang mereka pilih sehingga bisa menagih janji kampanye dan menilai kinerja pemimpin tersebut. Bahkan, rakyat memiliki “hak untuk menghukum” dengan tidak memilih kembali kepala daerah yang dianggap gagal menjalankan janjinya.
“Rakyat merasa punya sense of control, jika pilkada langsung, karena merasa bahwa dia telah memilih tentu juga dia bisa menagih janji kemudian juga menagih apa-apa yang dijanjikan selama masa kampanye,” ucap dia.
Sebaliknya, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, publik khawatir hubungan tersebut terputus. Kepala daerah dinilai akan lebih tunduk kepada partai politik daripada rakyat.
“Jadi, di mata publik, kalau dipilih langsung kepala daerah adalah milik rakyat. Kalau dipilih DPRD, kepala daerah dianggap milik partai, dan publik hanya menjadi penonton,” tegas Ardian.
Menurut LSI, keseluruhan faktor tersebut menjelaskan mengapa penolakan terhadap pilkada yang dipilih DPRD berlangsung secara luas dan kuat di masyarakat.




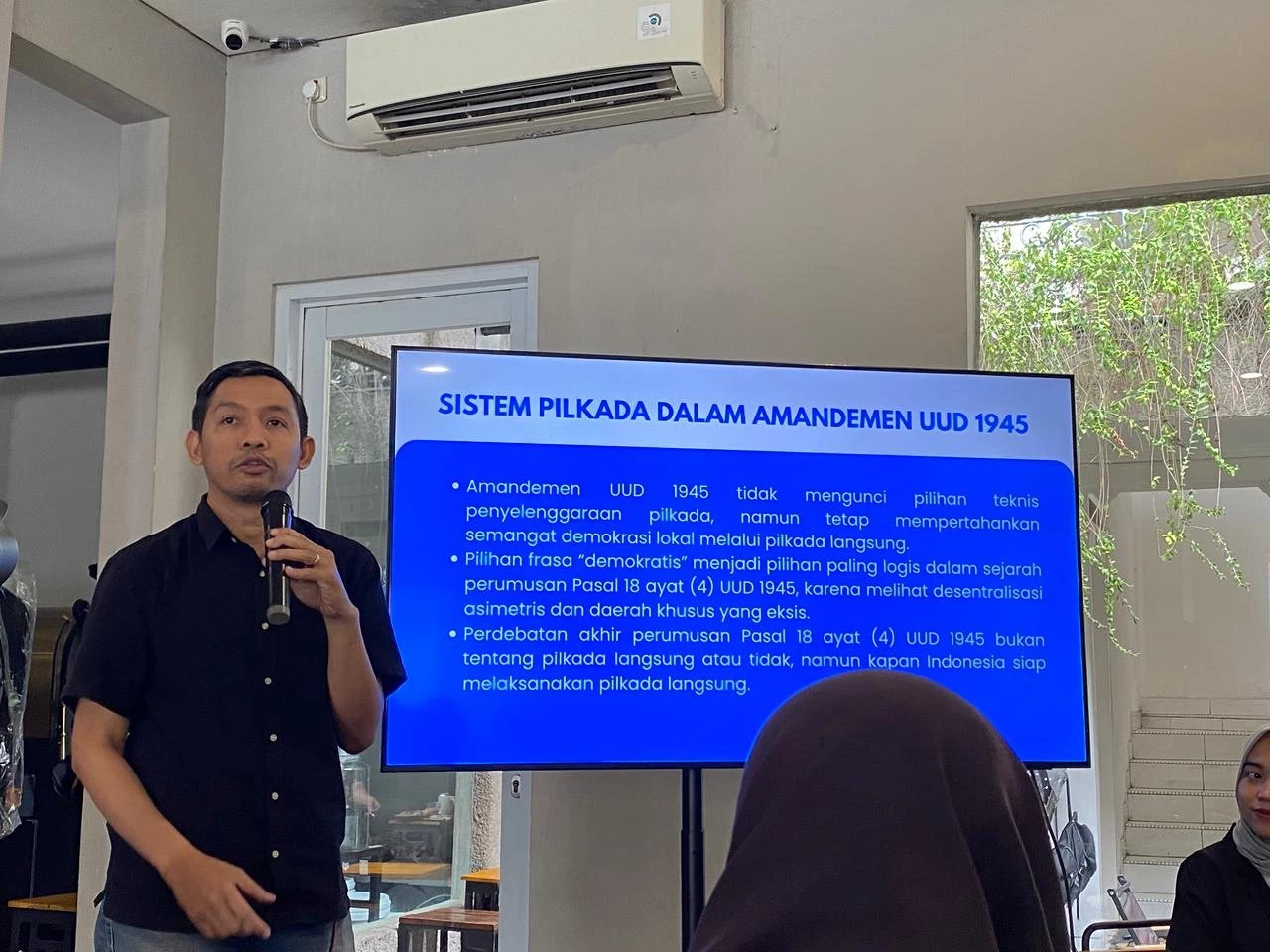
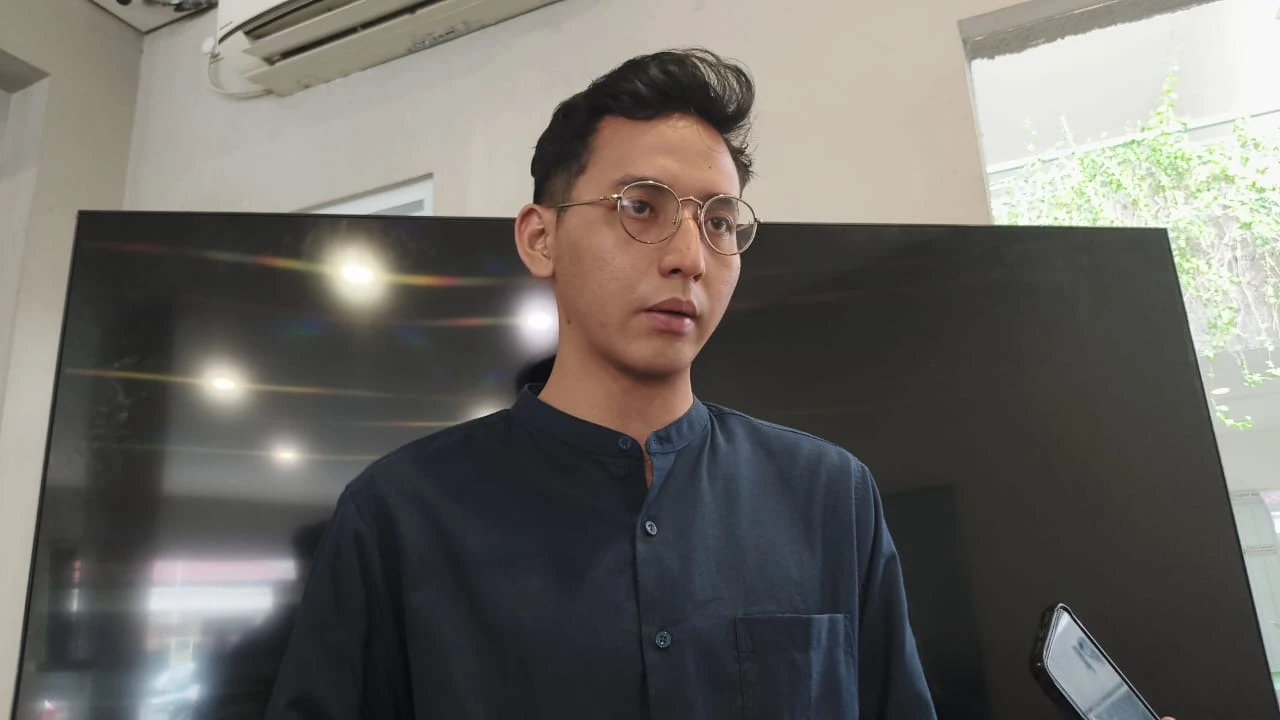



Tinggalkan Komentar
Komentar